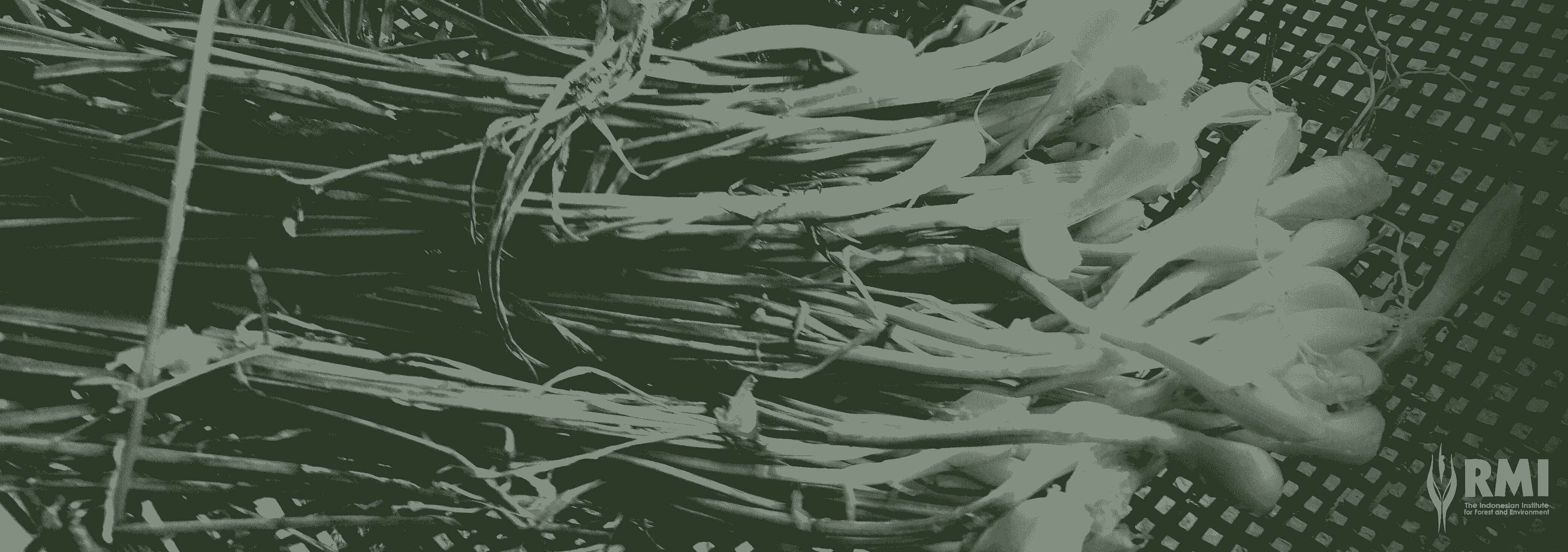Indonesia merupakan Negara Mega Biodiversitas dengan keanekaragaman hayati nomor dua tertinggi di dunia setelah Brazil. Tercatat sebanyak 15,3% keanekaragaman hayati berada di Indonesia[1]. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki sumber pangan, sumber obat-obatan, dan sumber ekologi yang lebih beragam dibandingkan dengan negara lain. Dalam buku Keanekaragaman Hayati, Amien S. Leksono mengatakan bahwa masyarakat Indonesia telah menggunakan 4.000 jenis tumbuhan dan hewan sebagai makanan, obat-obatan, atau produk lainnya[2]. Beberapa sumber pangan saat ini sudah sulit ditemukan karena jarang dimakan.
Untuk mengetahui keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan dan untuk menambah wawasan anak muda, Relawan 4 Life, sebuah gerakan anak muda dampingan RMI, mengadakan diskusi melalui Instagram Live. Diskusi diadakan bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia, 22 Mei 2020. Diskusi dipandu oleh Nadira Siti Nurfajrina, salah satu tim inti dari Relawan 4 Life, dan menghadirkan seorang narasumber, ahli pangan liar dan Founder Mantasa, Hayu Dyah. Awalnya, Hayu tertarik dengan pangan liar, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, namun masih banyak rakyatnya yang kelaparan. Maka ia mendirikan Mantasa, fokus pada pangan dari alam, agar masyarakat dapat mengkonsumsi keanekaragaman hayati yang jumlahnya banyak tersebut. Hutan, lahan basah, lahan gambut, termasuk juga mikroorganisme di dalam tanah, membuat tumbuhan liar bergizi, dan dapat dikonsumsi. Banyak masyarakat belum mengetahui, tumbuhan liar apa saja yang aman dikonsumsi dan memiliki kandungan yang baik untuk tubuh
Narasumber juga memberikan tips untuk memilih tanaman liar yang tidak beracun. Tanaman bisa dikatakan beracun jika warna dari buahnya itu cerah dan sangat kontras. Cara membedakan tanaman beracun, bisa juga dengan cara mencicipi tanaman tersebut. Jika terasa pahit, gatal, dan tidak enak, maka biasanya tanaman itu beracun.
Dijelaskan juga, hal dasar yang mempengaruhi menurunnya keanekaragaman hayati, karena adanya revolusi hijau. Revolusi hijau membuat petani menggunakan bibit dari pemerintah. Hal tersebut menyebabkan bibit lokal banyak yang punah karena tidak lagi dikonsumsi.
Kepunahan massal bisa terjadi kurang dari 30 tahun, bila kebijakan pemerintah mendukungnya. Ia pernah mewawancarai beberapa ibu di Flores tahun 1970-an. Pada masa itu ada program pemerintah tentang Rumah Sehat. Pemerintah menganggap rumah adat mereka tidak sehat. Rumah adat mereka berbentuk kotak, di tengahnya ada penyimpanan abu leluhur. Abu itu digunakan untuk mengawetkan benih, dan bahan pangan yang bersumber dari keanekaragaman hayati. Cara pengawetan benih secara tradisional ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi itu telah hilang ketika diberlakukannya program Rumah Sehat. Tidak hanya menghilangkan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghilangkan budaya dan identitas mereka.
Diskusi selama satu setengah jam berjalan cukup hangat dengan banyaknya tanggapan dari para peserta. Salah satu peserta menanggapi penjelasan warna tanaman liar yang lebih gelap, tidak seperti mie instan yang warnanya sangat banyak tergantung rasanya. Keinginan menulis buku sebagai pengetahuan bagi kaum muda, masih mengalami kendala, narasumber menjawab pertanyaan seorang peserta.
Pada akhir diskusi, narasumber berpesan agar kita memperhatikan bahan pangan seperti memperhatikan isi piring saat makan. Perhatikan berapa macam jenis pangan yang kita konsumsi dalam seminggu, dan mulai terhubung dengan alam dan tanah. Hal seperti itulah yang memberikan gizi pada tubuh kita. Ia mengingatkan agar tidak takut mencoba menu baru yang berasal dari alam. mengajak kita untuk mengkonsumsi bahan pangan sesuai musim.
Diskusi ini dapat dilihat di Instagram @relawan4life
[1] http://news.unpad.ac.id/?p=36173#:~:text=Sebanyak%205.131.100%20keanekaragaman%20hayati,3%25%20nya%20terdapat%20di%20Indonesia. Diakses pada 11 Juni 2020
[2] Leksono, A. S. (hal 115). 2010. Keanekaragaman Hayati. Malang: Universitas Brawijaya Press.
Penulis: Siti Marfu’ah
Editor: Shinta Miranda